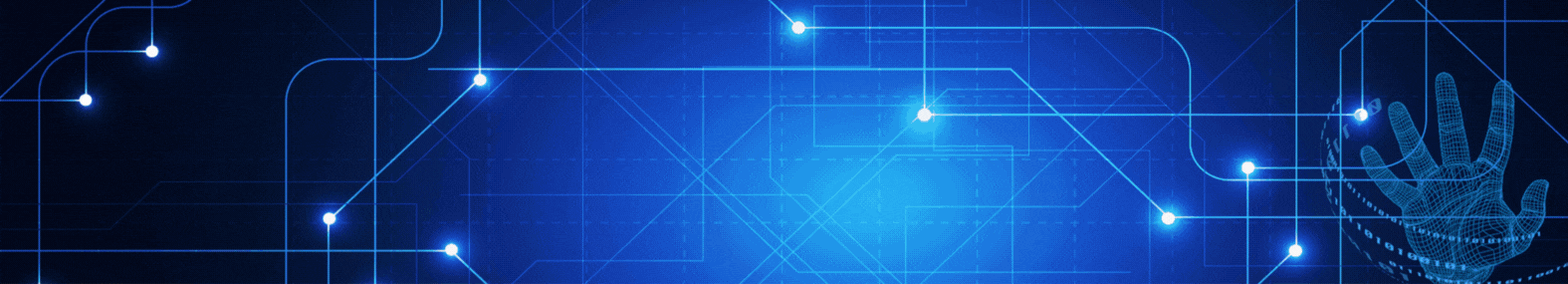Meski komunikasi kami tak lagi seintens saat saya masih berkiprah di Bawaslu Kota Bontang, saya tetap menjaga hubungan baik dengan Dr. Saipul, S.Sos., M.Si., dosen Universitas Mulawarman sekaligus mantan Ketua Bawaslu Kaltim dua periode. Karena itu, ketika ia memberi kabar sedang berada di Bontang, sesibuk apa pun agenda, saya berusaha menyempatkan diri untuk menemaninya.
Rabu (17/12) malam, kami bertemu sambil ngopi di The Bahagia Kaffee. Turut hadir Muzarrobi Renfly, Ketua KPU Bontang, dan Aldy Artrian, Ketua Bawaslu Bontang. Suasananya cair. Obrolan mengalir ringan. Khas pertemuan lama yang tak perlu banyak basa-basi.
Namun ketika percakapan mulai menyentuh isu politik kebijakan, Aldy memilih menjaga posisi. Ia tertawa sambil menggeleng pelan. “Kalau soal itu, saya no comment ya,” ucapnya singkat. Sikap yang wajar bagi penyelenggara pemilu yang harus berdiri di jarak aman. Muzarobbi pun mengambil sikap serupa. Diskusi soal politik akhirnya lebih banyak saya lanjutkan bersama Saipul.
Isu yang kami bicarakan malam itu sebenarnya sudah lebih dulu ramai di ruang lain. Saya tergabung dalam sebuah grup WhatsApp jurnalis nasional bersama Perludem, bernama Jaringan Pemilu. Beberapa hari terakhir, grup itu dipenuhi pertanyaan yang sama. Wacana mengembalikan pemilihan presiden dan kepala daerah ke DPR RI dan DPRD. Apakah demokrasi langsung dianggap gagal? Apakah efisiensi dijadikan alasan sah untuk menarik kembali hak pilih rakyat?
Wacana ini menguat setelah disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto dalam sejumlah pernyataan yang membuka ruang diskusi tentang kemungkinan mengembalikan pemilihan presiden dan kepala daerah ke mekanisme perwakilan. Pernyataan itu segera memantik respons luas—dari politisi, akademisi, pegiat demokrasi, hingga jurnalis. Bukan semata karena substansinya, tetapi karena sinyal tersebut datang dari Presiden.
Diskusi yang mengemuka di Jaringan Pemilu itulah yang membuat saya semakin tertarik mendengar pandangan Saipul secara langsung.
Saipul memulai dari sejarah. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, kata Saipul, bukan hal baru. Indonesia sudah pernah mengalaminya, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Bahkan menjelang runtuhnya Orde Baru, mekanisme pemilihan melalui DPRD sudah berjalan cukup luas.
Masalahnya, pengalaman itu meninggalkan catatan pahit. Kepala daerah yang dipilih DPRD cenderung lebih loyal kepada pihak yang memilihnya, bukan kepada rakyat. Kepentingan publik kerap tersisih karena pertanggungjawaban politik berhenti di ruang-ruang elite.
Fakta itulah yang kemudian melahirkan tuntutan Reformasi 1998. Kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat agar mandatnya jelas dan keberpihakannya terukur.
Pilkada langsung mulai dijalankan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diimplementasikan pada 2005. Kaltim termasuk daerah awal yang melaksanakannya. Tentu saja sistem ini tidak steril dari masalah. Politik uang, konflik, dan partisipasi yang fluktuatif adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri.
Namun menurut Saipul, persoalan itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menarik kembali kedaulatan rakyat. Justru sejak awal, ia melihat ada ketidakikhlasan elite politik terhadap pilkada langsung. Undang-undang tahun 2014 yang sempat mengembalikan pilkada ke DPRD menjadi bukti.
Reaksi publik kala itu keras. Demonstrasi mahasiswa, kritik akademisi, penolakan pegiat pemilu. Pemerintah akhirnya menerbitkan Perppu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan menandai pilkada serentak langsung.
Dalam pandangan Saipul, setiap kali pilkada bermasalah, sasaran kritik selalu mengarah ke rakyat atau penyelenggara. Padahal hulunya sering justru berada di partai politik. Partai menentukan calon dari tingkat pusat, bukan dari aspirasi daerah. Ketika kandidat yang diusung tidak dikehendaki publik, partisipasi menurun adalah konsekuensi logis.

Soal manipulasi politik pun demikian. Mayoritas kandidat pemenang berasal dari partai. Mesin kampanye, tim sukses, hingga praktik curang di lapangan juga digerakkan oleh struktur partai. Sementara calon perseorangan jumlahnya sangat kecil dan hampir selalu kalah.
Persoalan profesionalitas penyelenggara, menurut Saipul, juga kerap dibaca secara tidak adil. Penyelenggara ad hoc dibayar minim, dituntut bekerja profesional di bawah tekanan politik yang kuat, lalu disalahkan ketika sistem tidak ideal. Belum lagi proses pembekalan dan rekrutmen yang sering kali lebih mempertimbangkan afiliasi dibanding kapasitas.
Pandangan itu mendapat penguatan dari diskusi di grup Jaringan Pemilu. Salah satu respons yang cukup komprehensif datang dari Haekal, peneliti Perludem.
Ia menegaskan bahwa kualitas dan integritas calon kepala daerah pada prinsipnya sangat ditentukan oleh proses kaderisasi dan kandidasi di partai politik.
Masalahnya, proses itu hari ini banyak yang tidak berjalan. Popularitas dan kemampuan finansial sering kali lebih menentukan dibanding kapasitas dan rekam jejak.
Karena itu, menurut Haekal, keliru jika kegagalan tersebut lalu dibebankan kepada sistem pilkada langsung.
Ia juga menggarisbawahi soal mahalnya biaya politik. Biaya tinggi dalam pilkada bukan disebabkan oleh mekanisme pemilihan langsung, melainkan oleh biaya politik “gelap” yang mendominasi kontestasi.
Pertanyaannya, apakah jika pemilihan dikembalikan ke DPRD persoalan itu otomatis selesai? Jawabannya tidak! Selama watak politik partai masih sama, perubahan sistem hanya akan memindahkan biaya politik gelap ke DPRD dan justru memperparah wajah demokrasi lokal.
Haekal menutup dengan catatan penting: tidak ada jaminan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghasilkan pemimpin yang lebih berintegritas. Bahkan kecenderungannya adalah meningkatnya transaksi politik di ruang tertutup yang pada akhirnya menyandera kepala daerah ketika menjabat.
Dari meja kopi di Bontang hingga diskusi di grup Jaringan Pemilu, benang merahnya jelas. Kritik terhadap pilkada langsung sah dan perlu. Tetapi solusi dengan menarik kembali kedaulatan rakyat ke ruang elite, tanpa membenahi partai politik dan tata kelola kekuasaan, bukanlah jawaban.
Jika persoalan hulunya adalah partai politik, maka memperbaiki demokrasi seharusnya dimulai dari sana. Bukan dengan memotong hak rakyat untuk memilih, lalu berharap hasilnya otomatis lebih baik.
Sejarah sudah memberi pelajaran. Kita pernah mencoba. Kita tahu hasilnya. Mengulanginya dengan dalih efisiensi hanya akan membawa kita mundur, bukan maju.
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.