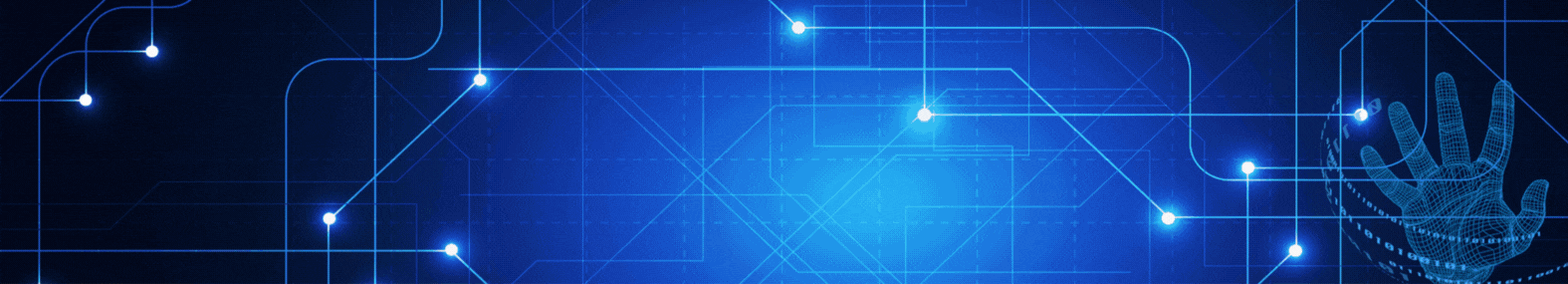SUARA dari aktivis dan praktisi turut mewarnai sesi FGD “Validasi Naskah Kodifikasi UU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil” di Hotel Aston Samarinda, Kamis (30/10). Jika dua tulisan sebelumnya banyak menyoroti aspek akademik dan kelembagaan, seri ketiga ini menyoroti pengalaman praktis di lapangan. Topik yang dibahas meliputi kaderisasi politik, rekrutmen penyelenggara, penegakan hukum, hingga efisiensi demokrasi.
Dian dari Koalisi Perempuan Indonesia mengingatkan bahwa kuota 30 persen perempuan sering kali berhenti di atas kertas. Di lapangan, perempuan kerap hanya “dicomot” menjelang pendaftaran tanpa proses kaderisasi yang matang.
Partai politik diminta menyiapkan kader perempuan sejak dini, minimal dua hingga tiga tahun sebelum pemilu serta memberi posisi strategis di daftar calon agar peluang keterpilihan nyata, bukan sekadar simbolik. Dian juga menegaskan pentingnya memastikan perempuan hadir sebagai pelaku dalam forum politik dan pengambilan keputusan, bukan pelengkap formalitas.


Sementara itu, Budiman dari FISIP Universitas Mulawarman menawarkan instrumen afirmatif yang lebih konkret: penerapan sistem proporsional dengan daftar tertutup (nomor urut tetap) yang dapat menjamin posisi perempuan tidak tersingkir oleh kompetisi terbuka berbiaya tinggi.
Ia juga mendorong penurunan ambang batas pencalonan presiden agar sirkulasi elite lebih terbuka dan tidak hanya dikuasai koalisi besar. Selain itu, pembatasan pendaftaran pemilih 60 hari sebelum hari H dianggap realistis dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Istilah “mandiri” pada penyelenggara, kata Budiman, sebaiknya diganti menjadi “independen” agar tidak menimbulkan tafsir ganda.

Nada lebih keras muncul dari Buyung, perwakilan Pokja 30 Kaltim. Ia menilai demokrasi di Indonesia masih terlalu mahal akibat logistikisme yang berlebihan. Dari tinta, kertas, hingga paku, semua membentuk ekosistem bisnis yang sulit disentuh efisiensi. Buyung mendorong adanya evaluasi berani terhadap jenjang politik yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik. “Belanja demokrasi harus ditimbang dari manfaatnya, bukan rutinitasnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Dosen Unmul Syaiful Bachtiar menyoroti akar masalah rekrutmen penyelenggara pemilu. Mantan Ketua Bawaslu Kaltim dua periode ini menekankan pentingnya pagar etik bagi tim seleksi di tingkat pusat dan daerah. Larangan mutasi lintas provinsi tanpa jeda, domisili minimal dua tahun, dan prasyarat pengalaman kepemiluan yang jelas harus ditegakkan.
Ia juga mengusulkan jenjang karier berlapis, anggota KPU/Bawaslu RI berasal dari provinsi, dan provinsi dari kabupaten/kota untuk mencegah “potong kompas” jabatan. Afirmasi perempuan harus bersifat mengikat, batas usia minimal dinaikkan (≥45 tahun di pusat; ≥40 tahun di provinsi) untuk memastikan kematangan etik, serta larangan hubungan darah antarpenyelenggara atau dengan pengurus partai guna menutup potensi konflik kepentingan.
Dalam aspek penegakan hukum, Syaiful menekankan perlunya memperkuat peran Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu, katanya, harus berwenang menetapkan dan memublikasikan status perkara secara terbuka, apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak, sebelum diteruskan ke penegak hukum. Skema ini diharapkan dapat memutus tarik-menarik politik yang kerap menghambat proses hukum. Untuk aspek etik, sanksi DKPP disarankan lebih progresif: dua kali pelanggaran berat seharusnya langsung berujung pada pemberhentian.
Ia juga menilai bahwa untuk tingkat kabupaten/kota, kelembagaan ad hoc masih relevan selama tahapan pemilu kini berlangsung dua kali (nasional dan daerah), karena lebih efisien secara anggaran. Di sisi partai, masa keanggotaan minimal sebelum dicalonkan perlu diperketat agar partai tidak berubah menjadi “rental politik” musiman yang hanya menampung figur berbiaya tinggi.
Pandangan tambahan juga datang dari jurnalis dan praktisi pengawasan pemilu. Ibrahim, Pemimpin Redaksi Kaltim Today, menyoroti lemahnya keterbukaan dalam laporan dana kampanye. Menurutnya, publik masih sulit mengakses data sumber dan aliran dana peserta pemilu, padahal transparansi menjadi bagian penting dari integritas demokrasi. “Peserta pemilu jarang memublikasikan dana kampanye secara terbuka,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi jurnalis yang meliput tahapan pemilu, mengingat banyak kasus intimidasi saat wartawan mengungkap dugaan pelanggaran partai atau kandidat.
Dalam forum yang sama, saya turut berbagi pandangan berdasarkan pengalaman sebagai anggota Bawaslu Kota Bontang periode sebelumnya. Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pemilu dan pilkada adalah keterbatasan waktu penanganan perkara. Dalam konteks Pilkada, Bawaslu hanya memiliki waktu 3 hari untuk kajian awal dan 2 hari untuk pembahasan di Sentra Gakkumdu (3+2 hari). Sedangkan untuk Pemilu, batas waktunya 14 hari kalender.
Durasi yang sangat singkat ini sering membuat perkara berhenti di tengah jalan, bukan karena tidak ada pelanggaran, melainkan karena alat bukti tidak cukup terkumpul dalam waktu sesempit itu.
Padahal, sebagian pelanggaran melibatkan aktor politik besar yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk penelusuran lapangan dan verifikasi saksi. Dalam kondisi seperti ini, Bawaslu berada di posisi dilematis: antara dikejar tenggat waktu dan tekanan politik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Saya menekankan pentingnya penguatan kewenangan Bawaslu dalam revisi undang-undang agar lembaga ini memiliki ruang yang lebih besar dalam proses penindakan, terutama dalam hal pembuktian dan penyidikan awal.
Bawaslu juga perlu diberikan dasar hukum yang lebih tegas untuk melanjutkan penanganan perkara tanpa rasa takut terhadap tekanan politik, khususnya ketika yang diproses adalah figur partai. “Jika Bawaslu hanya diposisikan sebagai pengawas administratif tanpa dukungan waktu dan kewenangan yang memadai, maka keadilan elektoral sulit ditegakkan,” saya tegaskan dalam forum tersebut.
Benang merah dari sesi ketiga ini semakin jelas: kodifikasi hukum pemilu tidak akan bermakna tanpa pembenahan menyeluruh terhadap ekosistemnya, mulai dari kaderisasi perempuan yang masih formalitas, rekrutmen penyelenggara yang longgar, mekanisme Gakkumdu yang belum transparan, hingga sistem penegakan hukum yang dibatasi waktu dan rentan terhadap tekanan politik. (bersambung)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.