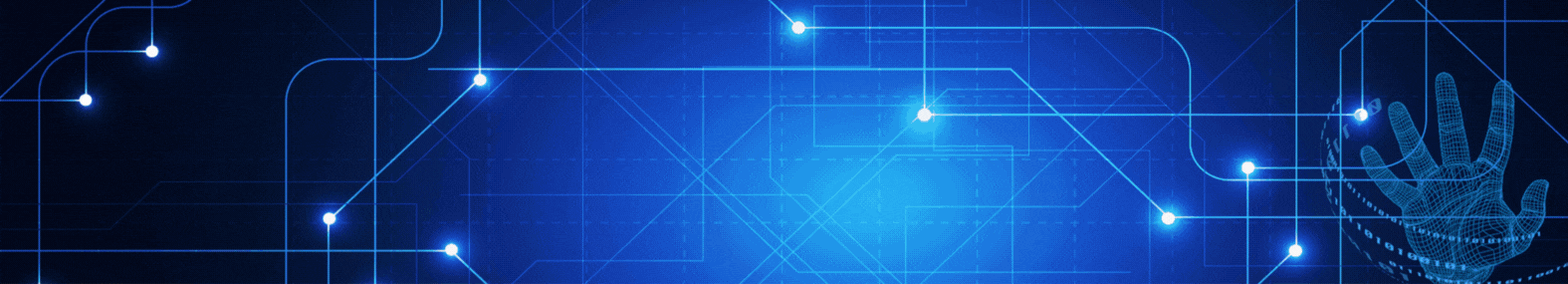ADA satu hal yang selalu menghantui para pemimpin di negeri ini: ketakutan mengambil keputusan. Saya ikut menyaksikan dan memberitakan bagaimana banyak pejabat BUMN, kepala dinas, hingga direksi perusahaan negara memilih diam, menunda, atau bermain aman. Bukan karena mereka tidak mampu. Tetapi karena mereka takut salah langkah. Takut diperlakukan seperti penjahat atas keputusan bisnis yang di tempat lain justru dianggap keberanian.
Kasus Ira Puspadewi kembali membuka luka lama itu. Sama seperti Dahlan Iskan—mantan Menteri BUMN sekaligus mantan Direktur Utama PLN—yang bertahun-tahun lalu berani menabrak kebekuan birokrasi demi efisiensi, tetapi justru harus berhadapan dengan dakwaan. Padahal rekam jejaknya dalam memajukan PLN dan mendorong keberanian pengambilan keputusan di kementerian BUMN sudah jelas dan nyata.
Padahal, merekalah orang-orang yang mencoba membetulkan arah kapal, mengambil risiko, dan menjalankan tugas yang tidak mau disentuh banyak orang. Namun ironi di negeri ini: orang yang berani mengubah justru lebih cepat menjadi tersangka dibanding mereka yang memilih tidak melakukan apa-apa.
Karena itulah, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang pada, Selasa (25/11/2025) kemarin, meneken rehabilitasi bagi tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry—termasuk Ira Puspadewi—menjadi isyarat kuat bahwa tidak semua perkara yang dibungkus istilah “kerugian negara” layak disebut korupsi.
Dari awal, perkara ini terasa janggal. Tuduhannya besar. Angkanya triliunan. Namun tak ada bukti satu rupiah pun mengalir ke para terdakwa. Kasus seperti ini justru lebih sering menghukum keberanian mengambil keputusan, bukan menghukum niat jahat. Dan itu masalah serius bagi iklim keberanian di birokrasi kita.
Saya mengikuti perkara ini. Apalagi kasusnya berulang kali muncul di beranda TikTok saya. Terlalu banyak tanda tanya yang menggantung. Mengapa direksi BUMN yang menjalankan aksi korporasi dengan appraisal independen, kajian bisnis lengkap, dan persetujuan pemegang saham bisa berubah menjadi terdakwa? Mengapa keputusan bisnis yang lumrah di banyak korporasi negara justru diseret menjadi tindak pidana?
Pertanyaan-pertanyaan itu semakin relevan ketika Ketua Majelis Hakim Sunoto menyampaikan dissenting opinion yang terang benderang: “Unsur korupsi tidak terbukti secara meyakinkan. Ini adalah business judgement.”
Hakim anggota lain pun mengakui bahwa ketiga terdakwa tidak menerima gratifikasi, tidak menerima uang, dan tidak memperkaya diri. Yang disorot hanyalah kelalaian prosedur. Jika kelalaian administratif dianggap korupsi, maka ratusan direksi BUMN bisa dipenjara esok pagi tanpa perlu penyidikan panjang. Namun logika seperti ini justru sering dipraktikkan: menghukum keputusan, bukan niat.
Bagian paling menggugah dari kasus ini justru muncul dari suara Ira sendiri. Di media sosial, sebelum rehabilitasi diumumkan, ia menulis dengan nada getir bahwa ia merasa dihukum bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena keberaniannya merapikan tata kelola ASDP.
Ia menjelaskan bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara merupakan keputusan profesional berdasarkan appraisal independen, bukan keputusan sembrono. Ia juga mengungkapkan rasa kecewa karena seluruh prestasi ASDP selama ia pimpin—mulai dari digitalisasi Ferizy, peningkatan kinerja, hingga laba tertinggi sepanjang sejarah ASDP pada 2023—tak pernah masuk dalam pertimbangan hukum. “Semua baik yang kami lakukan seolah hilang dalam satu narasi tuduhan,” tulisnya.
Dalam unggahan lain, ia menggambarkan bagaimana status tersangka mengubah hidupnya secara drastis. Reputasi yang ia bangun selama puluhan tahun runtuh dalam hitungan hari. Keluarganya, terutama anak-anaknya, menjadi sasaran cibiran publik.
Di satu kalimat yang paling menyentuh, ia menulis: “Saya tidak takut mati, tapi saya takut dihukum atas sesuatu yang tidak pernah saya lakukan.” Itu adalah suara seseorang yang merasa diperlakukan bukan sebagai pemimpin yang bekerja, tetapi sebagai penjahat yang diburu.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Ira Puspadewi itu? Ia bukan pejabat karbitan. Ia perempuan yang menempa kariernya dari bawah. Lulusan Universitas Brawijaya, meraih gelar master di Asian Institute of Management Filipina, bekerja sembilan tahun di GAP Inc Amerika Serikat sebagai direktur regional, lalu memimpin Sarinah dan Pos Indonesia sebelum dipercaya menakhodai ASDP. Di ASDP, ia membawa perubahan besar. Digitalisasi, efisiensi rute, penataan armada, hingga capaian laba tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Namun, seperti banyak reformis lainnya, semakin ia mempercepat perubahan, semakin banyak pula kepentingan yang merasa terganggu.
DPR RI sebenarnya sudah lama mencium kejanggalan dalam kasus ini. Keluhan masyarakat yang masuk pada Juli 2024 menunjukkan adanya proses yang tidak semestinya. Komisi III melakukan kajian hukum, dan hasilnya dikirimkan ke Presiden. Langkah ini bukan hal biasa; DPR hanya mengeluarkan rekomendasi ketika mendeteksi sesuatu yang tidak wajar dalam penegakan hukum. Dan pada akhirnya, Presiden menggunakan hak rehabilitasi. Ini pengakuan negara bahwa ada kekeliruan atau setidaknya keraguan serius dalam penanganan perkara tersebut.
Keputusan ini sekaligus menjadi kritik halus terhadap pola penegakan hukum kita yang terlalu sibuk mengejar angka “kerugian negara” daripada membedakan mana manuver korporasi yang legitimate dan mana tindakan yang benar-benar jahat. Jika moral hukum seperti ini dibiarkan, maka BUMN akan dipimpin oleh generasi pejabat yang hanya mencari aman, tidak berani mengambil risiko, hanya menunggu perintah, dan tidak berani membuat gebrakan.
Kasus Ira Puspa menunjukkan betapa sempitnya penilaian terhadap keputusan bisnis bisa menghancurkan reputasi, keluarga, dan keberanian mengambil risiko. Rehabilitasi memang memulihkan nama, tetapi tidak menghapus luka yang sudah terlanjur dibuat. Yang jelas, hukum tidak boleh menjadi alat untuk menjatuhkan orang yang bekerja dengan itikad baik.
Pada akhirnya, sejarah akan menilai. Dan hari ini, negara setidaknya mulai membenahi kekeliruan yang sudah terlalu lama dibiarkan. (*)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.