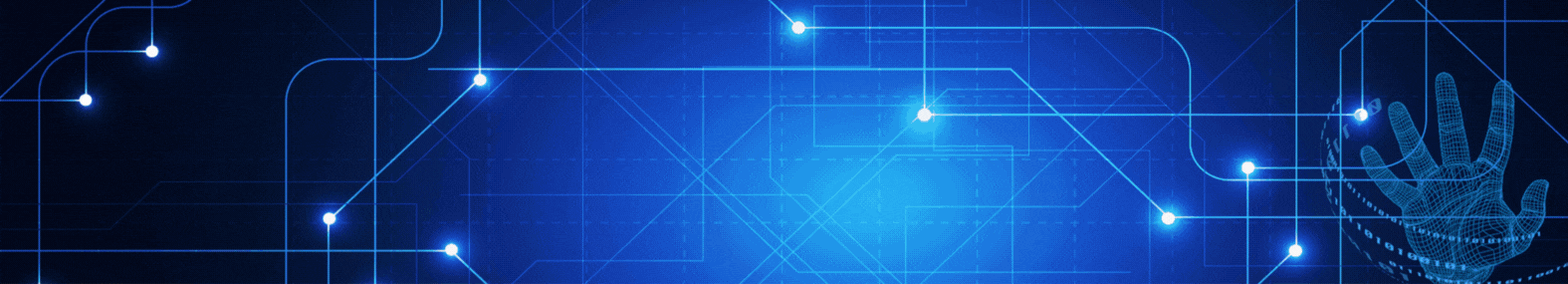HARI terakhir, Minggu (9/11), saya memulai pagi dengan langkah santai. Tidak ada target khusus selain menikmati sisa waktu di Singapura dengan cara berjalan, melihat, dan menyerap suasana. Dari Hotel Boss, saya dan istri berjalan kaki menuju Kampong Glam.
Pagi itu udara masih lembut. Toko-toko mulai membuka pintu, dan lorong-lorong kecil Arab Street dipenuhi wangi roti panggang dan teh hangat. Kami sarapan di salah satu kafe kecil: satu nasi goreng ayam kampung, dua set roti bakar dengan telur setengah matang, dan teh susu panas atau teh tarik. Kalau dirupiahkan sekitar dua ratus ribuan. Angka yang cukup lumrah di Singapura. Tapi suasananya membuat semuanya terasa pas.

Dari sana, kami menuju Masjid Sultan. Kubah emas masjid itu terlihat dari kejauhan, berdiri megah di tengah kawasan Bugis. Halamannya penuh wisatawan dari berbagai negara; sebagian memakai jubah yang dipinjamkan pengurus masjid.
Saya memotret beberapa sudut yang menenangkan: lorong dengan kipas langit-langit yang berputar pelan, deretan rak buku kecil di area pengunjung, hingga kelompok turis yang mendengarkan penjelasan tentang sejarah Islam di Singapura.
Di dalam masjid ada mesin cenderamata. Saya membeli satu coin bergambar Masjid Sultan—12 USD atau sekitar Rp144 ribu. Mahal, tapi sebagai jejak perjalanan, rasanya wajar.
Keluar dari kompleks masjid, kami berjalan ke Haji Lane. Lorong sempit penuh mural warna-warni, toko-toko indie, dan butik kecil yang menjual pakaian unik. Turis muda berseliweran. Sebagian sibuk berfoto; sebagian lain duduk di bangku kecil sambil memegang kopi dari kafe terdekat.

Saya sempat berbincang dengan dua wisatawan Indonesia dari Medan. “Bang, di sini enak kali buat cuci mata. Harga tetap Singapura, tapi suasananya bikin lupa capek,” kata mereka sambil tertawa. Tak jauh dari situ, wisatawan dari Surabaya menimpali, “Singapura tuh rapi banget. Serasa rumah kedua, cuma dompet harus kuat.”
Menjelang siang, kami bergerak ke arah barat kota menuju kawasan JEM dan IMM, dua mal besar yang terhubung jembatan. Suasananya ramai, tapi tertib. Saya langsung masuk Adidas karena sedang ada promo besar: beli tiga barang, diskon 50%. Mumpung cocok dan harganya turun, saya ambil tiga sekalian.
Di kasir, saya bertemu keluarga dari Batam. Mereka bilang, “Pak, di IMM pilihannya lebih banyak dan ukuran lengkap. Makanya ramai orang Indonesia ke sini.” Memang benar—IMM terasa seperti pusat diskon besar yang tak ada habisnya.


Beberapa brand yang familiar di mal-mal Kaltim juga ada di sini: BreadTalk, sampai Bebek Goreng Pak Ndut pun ada. Kami sempat mampir beli roti sebelum melanjutkan keliling. Waktu berjalan cepat, dan tiba-tiba langit sore mulai berubah warna.
Kami makan malam di area mal, menikmati sisa waktu sambil menutup hari terakhir di Singapura. Tidak ada yang terburu-buru. Hanya duduk berdua dengan istri, berbagi cerita ringan sambil melihat orang-orang lalu-lalang. Turis yang menenteng belanjaan, pekerja yang baru pulang, dan keluarga kecil yang menikmati malam seperti kami.

Perjalanan masih panjang. Besok pagi kami akan meninggalkan Singapura menuju Kuala Lumpur lewat jalur darat. Cara yang belum pernah saya coba sebelumnya. Ada rasa penasaran, sekaligus antusias, karena jalur darat selalu menawarkan pemandangan dan dinamika yang berbeda.
Saya sudah beberapa kali ke Kuala Lumpur beberapa tahun lalu. Pernah masuk lewat jalur udara dari Balikpapan, pernah juga lewat jalur laut dari Nunukan. Setiap kedatangan selalu membawa cerita berbeda. Maka perjalanan kali ini membuat saya bertanya-tanya, seperti apa wajah Malaysia hari ini? Apakah kotanya berubah? Apakah ritmenya semakin cepat? Atau justru ada hal-hal baru yang menunggu untuk ditemukan? (bersambung)
Oleh: Agus Susanto S.Hut., S.H., M.H.