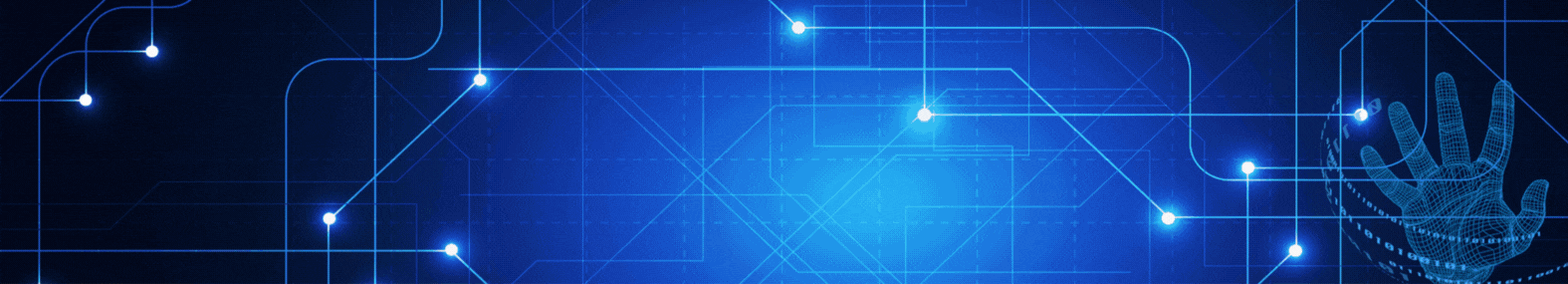Terakhir kali saya ke Singapura adalah tahun 2017, saat mengikuti kegiatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Batam. Usai acara, saya memutuskan menyeberang sendirian ke Singapura hanya untuk sehari. Pagi berangkat dari Pelabuhan Batam Center menuju HarbourFront Singapura, sore sudah kembali lagi ke Batam. Tidak ada agenda besar. Hanya ingin merasakan lagi sensasi naik MRT, menyusuri kota yang tertib, dan menikmati suasana taman-taman yang rapi.
Namun jauh sebelum itu, tahun 2013, saya pertama kali menginjakkan kaki di Singapura bersama rombongan kantor lama. Semua sudah diatur. Hotel, bus, hingga jadwal kunjungan semua sudah ditentukan. Hampir tak ada ruang untuk spontanitas. Tapi pengalaman itu cukup membuat saya kagum dengan keteraturan dan bersihnya kota ini.
Kali ini berbeda. Tidak ada tour guide, tidak ada rombongan, tidak ada agenda resmi. Semua saya atur sendiri. Mulai dari tiket, penginapan, hingga rencana perjalanan harian. Perjalanan mandiri yang saya jalani dengan rasa penasaran dan kebebasan penuh.
Perjalanan dimulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Jumat pagi (7/11), pesawat AirAsia yang saya tumpangi lepas landas pukul 07.00 WITA. Dua jam lebih sedikit kemudian, saya sudah mendarat di Bandara Internasional Changi (Changi Airport), bandara terbaik di dunia yang selalu memberi kesan efisien dan nyaman.
Jam di ponsel menunjukkan 09.30 waktu setempat, sama persis dengan waktu di Kaltim. Singapura memang berada di zona waktu UTC+8, sama seperti Balikpapan dan Samarinda. Hanya waktu salatnya yang sedikit lebih lama.
Sebelum berangkat, saya sudah menyiapkan semua dokumen penting: paspor, tiket, dan formulir ICA, formulir kedatangan elektronik yang wajib diisi secara online. Pengisian bisa dilakukan sejak tiga hari sebelum jadwal kedatangan hingga hari H penerbangan. Tanpa formulir ini, proses imigrasi bisa tertahan cukup lama.
Hal kecil lain yang juga perlu diperhatikan adalah aturan barang bawaan. Botol air minum, termasuk air mineral yang masih tersegel, tidak diperbolehkan melewati pemeriksaan keamanan. Sementara itu, powerbank dan perangkat elektronik tetap aman dibawa ke kabin, asalkan kapasitasnya sesuai ketentuan penerbangan.
Begitu keluar dari terminal, suasana Changi Airport langsung terasa. Bersih, teratur, dan nyaman. Petunjuk arah yang jelas membuat siapa pun mudah menavigasi diri. Di dekat pintu keluar, saya menukar sedikit uang ke dolar Singapura (SGD) di money changer bandara. Tak banyak, hanya cukup untuk ongkos taksi dan makan. Di negara ini, hampir semua transaksi bisa dilakukan secara non-tunai, tapi uang tunai tetap berguna untuk transportasi umum atau kios kecil.
Awalnya saya berencana naik MRT menuju hotel, tapi melihat koper yang cukup berat, akhirnya saya memesan Grab. Sopirnya, Mazzali Bin Khosairie, ternyata bisa berbahasa Indonesia. “Kalau dulu datang tahun 2013, pasti banyak yang berubah,” katanya tersenyum.
Saya menatap keluar jendela mobil. Benar saja, gedung-gedung baru berdiri, taman kota makin rapi, dan lalu lintas tetap tertib tanpa suara klakson. Singapura terasa seperti kota yang tak pernah berhenti berbenah.
Tiba di Hotel Boss sekitar pukul 11.00, saya tidak berharap bisa langsung check-in karena jadwalnya pukul 15.00. Namun petugas resepsionis yang ramah mengatakan ada kamar kosong yang bisa digunakan lebih awal. Keberuntungan kecil di negeri yang serba efisien ini.
Setelah beristirahat sejenak, saya bersiap menyeberang ke Masjid Malabar, yang berdiri megah tepat di seberang hotel.

Masjid ini tampak megah dengan dominasi warna biru dan kubah emas yang berkilau di bawah matahari siang. Di dalam, jamaah sudah mulai berdatangan untuk salat Jumat. Lantainya bersih, udara sejuk, dan suasana khidmat. Khutbah disampaikan dalam bahasa Inggris, sementara teksnya ditampilkan di layar agar mudah diikuti.
Di halaman masjid, panitia menyediakan air minum dan paket “Jumat Berkah”. Di sisi lain, pedagang menjual nasi briyani dan roti prata hangat.
Saya sempat berbincang dengan salah satu jamaah. Ia bercerita bagaimana komunitas Muslim di Singapura hidup berdampingan dengan masyarakat multiagama.
Usai salat dan istirahat sebentar, saya dan istri berjalan kaki menikmati suasana sekitar Bugis Street, pusat belanja murah yang tak pernah sepi. Di sinilah warna Singapura yang sesungguhnya terlihat: modern, tapi tetap punya sisi tradisional. Kios pakaian, makanan ringan, dan suvenir khas berjajar rapi. Harga masih ramah, asal pandai menawar.

Dari Bugis, saya melanjutkan perjalanan sore itu menggunakan MRT menuju Downtown Station di jalur biru (Downtown Line). Perjalanan hanya sekitar 10 menit. Dari sana, saya langsung berjalan kaki menuju kawasan Marina Bay untuk menikmati suasananya. Semua terasa mudah dan efisien.
Saya menggunakan EZ-Link Card, kartu serbaguna yang bisa dibeli di loket MRT seharga 10 dolar Singapura dengan saldo awal 5 dolar. Saya isi ulang lagi 10 dolar untuk berjaga. Rata-rata setiap perjalanan hanya menghabiskan 1,5–2 dolar, sekitar Rp25 ribu per orang.

Begitu keluar di area Marina Bay, suasananya luar biasa. Sore itu langit cerah, angin laut berembus lembut, dan ratusan wisatawan dari berbagai negara berkumpul di sekitar Merlion Park.
Di kejauhan, gedung Marina Bay Sands menjulang seperti kapal raksasa di atas tiga menara kaca. Di tepi promenade, sepasang musisi jalanan memainkan lagu lembut yang berpadu dengan suara air mancur dari mulut patung Merlion.
Saya dan istri berdiri di tepi pagar, menikmati pemandangan. Cahaya sore berubah keemasan, memantulkan siluet gedung-gedung tinggi yang tampak seperti lukisan hidup.

Menjelang petang, kami naik MRT menuju kawasan Expo. Tujuannya ke Changi City Point, mal yang berada tepat di sebelah stasiun Singapore Expo. Tempat ini dikenal dengan deretan factory outlet dan suasananya yang lebih santai. Saya hanya membeli ubi bakar besar seharga 5 dolar, tapi rasanya enak sekali setelah seharian berjalan kaki.
Malam mulai turun saat kami kembali ke Bugis. Di sekitar hotel, aroma nasi briyani dari kedai India memenuhi udara. Kami mampir sebentar untuk makan malam ringan sebelum beristirahat. Hari pertama di Singapura berakhir dengan tenang, tanpa hiruk-pikuk, hanya rasa syukur dan damai di tengah kota yang tak pernah benar-benar gelap. (bersambung)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.