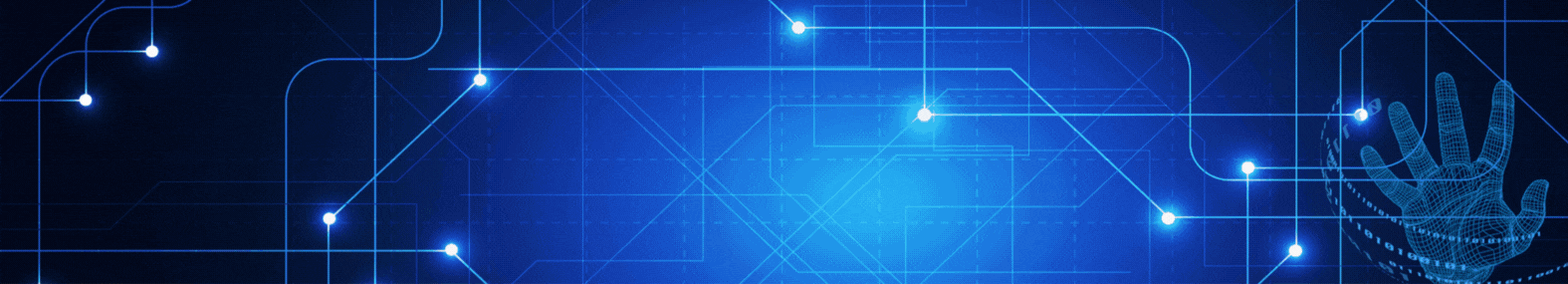SESI diskusi FGD “Validasi Naskah Kodifikasi UU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil” di Hotel Aston Samarinda, Kamis (30/10), berlangsung dinamis. Masukan datang dari kalangan akademisi, jurnalis, dan aktivis mahasiswa yang menyoroti aspek substansi dan implementasi rancangan undang-undang pemilu.
Alfian dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) memulai pandangannya dengan menegaskan pentingnya naskah akademik sebagai landasan konseptual sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ia menilai draf yang dibahas sudah cukup progresif karena menekankan jaminan hak politik dan kedaulatan warga, namun masih menyisakan pekerjaan rumah terkait konsistensi antarpasal dan kejelasan definisi.
Ia menyoroti formulasi pembagian kursi DPR “50 persen Jawa dan 50 persen luar Jawa.” Menurutnya, dikotomi berbasis pulau perlu disertai argumentasi kebijakan yang lebih kuat. “Kenapa bukan berdasarkan kepadatan penduduk, sebaran wilayah, atau indeks keterjangkauan? Ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan tafsir kebijakan yang sempit,” ujarnya.

Di tingkat daerah, pembagian kursi yang masih mengikuti pola lama juga dinilai belum selaras dengan semangat penataan representasi di pusat. Sementara itu, istilah “kelompok marginal dan minoritas” yang muncul di naskah tanpa penjelasan khusus disarankan agar didefinisikan secara eksplisit di bagian penjelasan untuk menghindari multitafsir dalam penerapan.
Dalam aspek tata kelola, Alfian menilai ketentuan konsultasi publik sebelum KPU dan Bawaslu menetapkan peraturan merupakan langkah maju. Frasa “dapat berkonsultasi dengan DPR” dianggap tepat karena menjaga ruang dialog tanpa mengganggu independensi lembaga penyelenggara. Ia juga mengingatkan agar metode kampanye tidak sekadar daftar istilah seperti “rapat umum” dan “dialog,” tapi dijabarkan batasan operasionalnya, termasuk alasan normatif jeda 12 jam antara penutupan kampanye dan hari pemungutan suara.
Soal pembiayaan, kewajiban audit dana kampanye dalam tenggat 14 hari diapresiasi karena memberikan kepastian waktu dan mendorong disiplin pembukuan.

Catatan kelembagaan datang dari Miftah, peneliti Pusat Studi Konstitusi, Demokrasi, dan Masyarakat UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Ia mengingatkan bahwa penempatan KPU sebagai “lembaga non-struktural” berpotensi menurunkan martabat kelembagaannya. “KPU seharusnya dipahami sebagai lembaga negara independen dengan karakter self-regulatory, bukan sekadar entitas di luar kementerian,” tegasnya.
Pada syarat calon anggota KPU dan Bawaslu, frasa “mengundurkan diri dari ormas setelah terpilih” dianggap membuka celah afiliasi selama proses seleksi. Miftah mengusulkan agar calon sudah bersih sejak pendaftaran, tidak menjadi pengurus atau anggota ormas dan partai politik, serta wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sejak awal untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan transparansi.
Isu politik uang juga mencuat dalam diskusi. Larangan yang hanya dikaitkan “saat pemungutan suara” dinilai terlalu sempit karena praktik transaksional justru marak sebelum hari pencoblosan. Forum merekomendasikan agar rumusan waktu diperluas dan sanksi disesuaikan proporsional, tanpa menjadikan semua pelanggaran bernuansa pidana.
Menjelang akhir sesi, forum masuk ke bahasan Putusan MK Nomor 135/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah. Tiga opsi yang muncul — PAW panjang, perpanjangan masa jabatan DPRD, dan pemilu sela — dianggap sama-sama berisiko menabrak prinsip masa jabatan lima tahun. Alfian menyarankan agar desain norma ditata ulang dan tafsir hukum diuji kembali, supaya penjadwalan jabatan DPRD tetap akuntabel dan operasional di lapangan tidak terganggu.
Pandangan kritis juga datang dari BEM Universitas Mulawarman dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Kedua organisasi ini meminta agar sebelum dilakukan revisi atau kodifikasi UU Pemilu, pemerintah dan DPR terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu sebelumnya.
“Evaluasi ini penting supaya perubahan undang-undang tidak hanya memoles teks hukum, tapi benar-benar memperbaiki praktik di lapangan, seperti akurasi DPT, transparansi rekapitulasi, dan distribusi logistik,” ujar perwakilan BEM Unmul. Sementara Jatam menekankan, evaluasi juga harus menyentuh sisi partisipasi publik, netralitas aparatur, dan dampak lingkungan dari proses politik yang sering kali abai pada prinsip keberlanjutan.
Dari rangkaian pandangan itu, garis besarnya jelas: kodifikasi merupakan langkah penting dan mendesak untuk memperkuat sistem kepemiluan nasional. Namun efektivitasnya hanya akan tercapai jika disertai kejelasan definisi, konsistensi norma, serta evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemilu sebelumnya. Naskah kodifikasi yang tengah disiapkan koalisi nasional bersama Perludem ini diharapkan menjadi rujukan bagi DPR RI dalam proses pembahasan undang-undang, apalagi hingga kini belum ada tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Dari beberapa pernyataan anggota DPR RI, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu baru akan dimulai pada tahun 2026 melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sementara pada tahun yang sama tahapan rekrutmen anggota KPU juga sudah dimulai. (bersambung)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.